Resensi : Burung-Burung Manyar
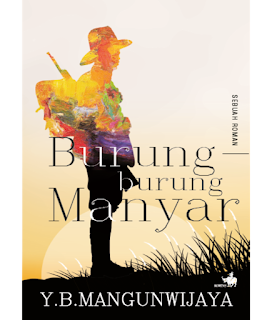
Sumber : gerai.kompas.id
Judul : Burung-Burung Manyar
Penulis : YB. Mangunwijaya
Tahun Terbit : Pertama kali diterbitkan 1981 oleh Penerbit Djambatan
Penerbit : Kompas
Tebal halaman : 406
Kalau saja nada tulisan dalam sebuah buku bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang saling berkebalikan, entah itu bernada membenci, bernada semangat 45, atau bernada sedih, mungkin tulisan Rama Mangun dalam buku ini mencakup semuanya. Ia bisa membawa nada bahagia, nada kebencian, atau nada kesedihan. Sebuah roman, begitu yang tertulis di kover depan buku ini, pun demikian isi keseluruhan cerita yang menggambarkan perjalanan hidup dan jatuh-bangun seorang tokoh bernama Setadewa. Bukan melulu roman yang berputar pada kisah percintaan, tapi lebih kepada roman kehidupan yang meliputi semua emosi yang pernah dirasakan manusia: bahagia, sedih, dan benci.
Pada bagian awal, Rama Mangun membuka cerita dengan sebuah prolog mengenai pewayangan, lebih tepatnya mengenai anak-anak Sri Baginda Raja Basudewa, Kakrasana dan Narayana. Kakrasana yang merupakan makhluk seta, serba putih segala-galanya, dan Narayana yang hitam legam tulang, daging, saraf, dan segala-galanya. Siapa sangka, saudara seayah yang beranjak dewasa, satunya berpihak Pandawa, dan satunya berpihak Kurawa. Narayana menjadi ahli siasat utama Pandawa, sedang Kakrasana yang serba putih memihak Kurawa demi kesetiaannya pada istrinya Herawati dan ayah mertua, Raja Salya dari Mandraka. Tetapi, dalam hatinya, kecintaan pada Pandawa tidak berhenti berpijar.
Setadewa adalah putra Kapitein Brajabasuki lulusan akademi Breda di Belanda, serta Maurice keturunan Indo-Belanda yang masih memiliki darah ningrat Jawa. Dipandang dari segi historis keluarga, mereka adalah keluarga yang dekat dengan pemerintah Belanda. Setadewa, atau Teto, tumbuh jauh dengan kehidupan kerajaan yang penuh basa-basi. Ia tumbuh sebagai 'anak kolong' bersama anak-anak kelas rendahan yang suka berenang di sungai. Praktis, Teto tumbuh diilhami dengan keberanian yang didapatnya selama bergaul dengan anak-anak pinggiran, membawa kepercayaan bahwa ia hidup bukan dengan uang, melainkan karena telah berbuat berani dengan kebanggaannya untuk membela apa yang ia anggap benar.
Masa kecil Teto tidak kekurangan apapun. Gejolak dalam hidup Teto dimulai ketika zaman pendudukan Jepang. Ayahnya yang menjadi buron, dan ibunya yang menjadi gundik Jepang, membawa hantaman besar untuk Teto, dan di situlah awal mula dari perjalanan panjang gejolak emosi yang dirasakan oleh Teto.
Di satu sisi, Atik yang merupakan teman kecil Teto, masih mampu berpegang teguh pada kewarasan dirinya hingga ia dewasa. Ia seperti arah mata angin yang berlawanan dengan Teto. Masa kecil mereka terpaut erat, tapi kehidupan mereka semakin jauh ketika beranjak dewasa. Dan Teto yang telah kehilangan segala pijakannya, yaitu ayah dan ibunya, hanya memiliki Atik sebagai pijakan masa lalunya, yang disayangkan, memiliki keberpihakan berbeda dengan apa yang diyakini oleh Teto.
Kisah ini sarat dengan pergolakan batin Teto. Ketika orangtuanya menghilang, kemudian ketika ia bergabung dengan KNIL, melakukan pekerjaan-pekerjaan bandit bersama Kolonel Verbruggen, menjadi tentara pro-Belanda ketika Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Pergolakan batin karena luka yang ia alami sejak kehilangan orangtua, luka yang menimbulkan dendam mendalam terhadap Jepang, serta luka setiap mengingat teman kecilnya--Atik--berada di pihak seberang, bekerja sebagai sekretaris Syahrir, sementara dirinya beranggapan bahwa Indonesia masih terlalu prematur untuk merdeka.
Sedikit ekstrim, barangkali, karena menampilkan tokoh utama sebagai pihak yang kontra terhadap kemerdekaan Indonesia. Tapi, pada akhirnya, prolog prawayang di bab pertama sungguh menggambarkan isi hati Teto dalam setiap perjalanannya, seperti Kakrasana yang berpihak Kurawa : dalam hati terdalamnya, meski berseragam KNIL, ia tak bersedia menyebut dirinya sebagai manusia yang meninggalkan negerinya sendiri.
Roman hidup Teto tidak banyak memiliki episode bahagia, dan tidak pula menemukan akhir bahagia. Pada akhirnya, Teto bertemu kembali dengan Atik yang bersuamikan orang lain. Keduanya hidup berdampingan selayaknya kakak-adik, tapi sepertinya perasaan Teto benar-benar dipermainkan tidak cukup hanya dengan menjadi seseorang yang kalah seumur hidupnya--kalah dalam adu keyakinan siapa yang akan memenangkan perang, kalah dalam menghadapi ketakutannya sendiri untuk menjemput Atik--tetapi juga dengan potongan episode paling akhir di mana akhirnya ia kehilangan Atik.
Pada akhirnya, setelah seumur hidup tidak bisa menerima kekalahannya, Teto mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Rama Mangun memberikan sebuah kisah hidup yang kaya pergolakan batin. Kisah dalam buku ini bernada kebencian hingga tiba pada bagian episode di mana Teto bertemu Atik. Teto yang legowo, Teto yang dewasa, Teto yang akhirnya bisa berdamai. Dan nuansa kedamaian itu muncul dalam sebuah narasi yang diucapkan oleh Atik dalam sidang doktornya.
"Maka jika kita pernah mengalami kegagalan, semogalah makhluk-makhluk burung mungil yang bernama Ploceus Manyar yang sekarang, sayang, namun juga untung bagi pak tani, sudah semakin hilang dari persada bumi Nusantara kita, semogalah burung-burung nakal, namun pewarta hikmah yang indah itu memberi kekuatan jiwa. Sebab memanglah kita dapat sedih dan marah membongkar segala yang kita anggap gagal, namun semogalah kita memiliki keberanian juga untuk memulai lagi dengan penuh harapan. Terimakasih." (p. 325)
Apabila dibaca sepotong-sepotong, akan ada lebih banyak lagi pesan dan hikmah yang disampaikan oleh Rama Mangun, tidak jauh-jauh dari kehidupan yang membawa napas dan citra orang Indonesia. Namun, secara keseluruhan, demikianlah isi buku ini, bercerita soal Teto si Anak Kolong, yang dengannya, Rama Mangun memberikan wejangan mengenai innerlichkeit. Jati diri. Bahasa citra. Sebuah bentuk pengejawantahan jati diri sebagai manusia.
Membingungkankah? Karena, sebenarnya, ketika ditilik dengan lebih seksama, Rama Mangun memberikan wejangan yang sama dalam bukunya yang lain, Wastu Citra. Sebuah buku pengantar pembelajaran kuliah beliau. Berbicara soal citra dan jati diri. Namun, terlepas topik apa yang beliau singgung dalam buku kuliah tersebut, sepertinya jati diri itu yang beliau coba sampaikan dalam kisah hidup Teto. Setiap pemikiran, setiap keputusan, tindakan, dengan siapa kita bergaul, di mana kita membawa diri, bagaimana masa lalu membentuk kita, bagaimana cara kita berjalan, berbicara, semuanya adalah bentuk citra. Sebuah bentuk pengejawantahan jati diri sebagai manusia.
Last but not least, ciri khas tulisan Rama Mangun sangatlah kentara. Di samping banyak sekali diksi khas pendudukan Belanda dan Jepang, Rama Mangun acapkali menggunakan diksi 'asli Indonesia'. Ah, bagaimana ya mendeskripsikannya. Diksi yang seringkali kita kira tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, namun ternyata ada. Mungkin lebih tepatnya seperti itu, menyebabkan pertanyaan-pertanyaan muncul di kepala, "Sudah sebecus apa kamu mempelajari bahasamu sendiri?"
Rahayu.

Komentar
Posting Komentar